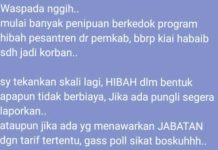Layaknya gula dan semut. Semakin banyak keistimewaan yang diperoleh, membuat semakin banyak orang kepincut.
Oleh : Gandha Widyo Prabowo*)
DATANG ke TPS, mencoblos, kemudian pulang. Setelah itu, apa yang terjadi pada diri kita?
Apakah elite eksekutif dan legislatif terpilih mewujudkan janji yang ditebarnya?
Apakah kualitas hidup kita meningkat?
Benarkah hidup kita menjadi lebih sejahtera?
Beberapa pertanyaan itulah yang sering mengemuka di obrolan warung kopi. Mereka sambat. Berkali-kali pemilu, berkali-kali pula tidak nampak hilal kesejahteraan. Anehnya, mereka yang sudah milih malah dijadikan kambing hitam untuk disalahkan. Mereka disalahkan karena pemimpin terpilih tidak bisa menghadirkan kenikmatan seperti yang sudah dijanjikan.
Pemilih dalam kondisi serba salah. Ketika mau lebih selektif memilih, ternyata kandidat wakil rakyat yang ditawarkan terbatas. Sebaliknya, ketika memutuskan tidak memilih, malah dianggap sebagai warga negara yang tidak bertanggungjawab. Ngerinya lagi, bahkan difatwa berdosa kalau sampai golput.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU tidak bisa berbuat banyak mengatasi persoalan ini. KPU an-sich melaksanakan pemilu berdasarkan peraturan yang ditetapkan pembuat undang-undang.
Kewajiban moral KPU hanya mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan memahamkan pemilih agar tidak terseret praktik politik uang (money politic).
Pertanyaannya, siapa yang menjamin tidak ada politik transaksional di dalam pemilu?
Praktik politik uang ibarat kentut. Baunya menyengat, tapi tak ada yang tahu sejatinya pemilik kentut tersebut. Lihat saja, dalam pelaksanaan pemilu di berbagai daerah.
Intensitas pemilu atau pemilihan yang begitu banyak digelar, ternyata jumlah pelaku politik uang yang terungkap hanya sedikit. Padahal, dugaan praktik politik uang masih hadir dan membayangi di setiap pemilu.
Kita tahu biaya pemilu tidaklah murah. Apalagi ketika menjadi peserta pemilu. Ada biaya politik yang dikeluarkan dan itu tidak sedikit (high cost).
Misalnya, untuk pembiayaan kegiatan kampanye. Mau tidak mau, peserta pemilu harus merogoh koceknya lebih dalam. Biaya jasa manajerial kampanye (tim sukses), pembuatan spanduk, selebaran, biaya jasa konsultan politik, dan segala pengeluaran lain untuk meyakinkan pemilih.
Belum lagi biaya ‘kendaraan’ partai politik. Ongkosnya bisa lebih besar lagi. Sebab, ada kontribusi yang mesti diserahkan. Jenis dan besaran kontribusi yang ditetapkan juga beragam. Tergantung seberapa tinggi tingkat keterpilihan kontestan menjadi anggota legislatif atau eksekutif. Untung saja, praktik mahar ini perlahan mulai ditinggalkan. Beberapa partai politik meng-klaim partainya nihil mahar.
Biaya-biaya yang dikeluarkan ini tentu saja menjadi bagian dari modal. Selayaknya hukum pasar, modal yang dikeluarkan tentu harus kembali. Tapi, semua orang paham, jika modal yang dikeluarkan pasti kembali ketika sudah berhasil mendapatkan kursi. Tidak hanya modal, bahkan ada banyak keistimewaan (privilege) yang akan dinikmati.
Otomatis penghasilan yang diperoleh cukup besar. Keistimewaan lainnya seperti mendapatkan fasilitas kendaraan dinas. Punya kewenangan yang besar. Dan segudang untung lainnya. Layaknya gula dan semut. Semakin banyak keistimewaan yang diperoleh, membuat semakin banyak orang kepincut.
Menjadi ironi ketika tergiur dengan keuntungan yang akan diperoleh, kontestan lalu berkiblat pada ajaran Machiavelli. Segala cara dihalalkan untuk meraih kekuasaan. Mereka mengambil jalur pintas dengan membeli suara pemilih. Akhirnya, terjadi fenomena ‘satu orang satu suara satu nilai satu uang’ (One Person One Vote One Value One Money).
Lantas, siapa yang bisa membendungnya ketika sudah menjadi sebuah keniscayaan?
Masyarakat yang merasa tidak mendapat manfaat dari pemilu merasa apatis. Uluran uang atau barang dari kandidat mereka terima saja.
Akhirnya, terjadilah transaksi jual beli suara. Parahnya, perilaku ini disemaikan terus-menerus di setiap pemilu ke pemilu. Sehingga, menjelang hari-H coblosan, tak jarang di kampung dan di sudut gang perumahan bergerombol warga menanti serangan fajar.
Ketika politik transaksional masih terus muncul, maka sulit membayangkan output dari pemilu adalah pemimpin yang berkualitas dan berpihak pada rakyat. Bisa jadi, pemimpin ini malah menghamba pada kekuatan pemodal yang jadi penyokongnya.
Lihat saja konflik-konflik horisontal yang muncul di berbagai daerah. Tak jarang malah elite pemimpinnya yang menjadi sumber permasalahan. Entah karena mengeluarkan regulasi yang menguntungkan pemilik modal atau karena berlaku diskriminatif saat melayani masyarakat kecil.
Namun demikian, politik transaksional bisa diredam jika seluruh stakeholder mau merubah mindset-nya tentang pemilu. Mencoba memaknai kembali pemilu sesuai dengan khittah-nya.
Tidak hanya menganggap pemilu secara prosedural: datang-coblos-pulang. Tetapi, lebih ke makna filosofis pemilu. Yakni, sebuah proses pergantian elite kepemimpinan yang tujuan akhirnya untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara.
Makna filosofis ini bukanlah seperti gagasan utopis Karl Marx saat mencetuskan ide masyarakat tanpa kelas yang terbukti gagal.
Elite politik harus merubah sikap perilakunya untuk menggapai makna filosofis pemilu. Dari sikap mental ingin dilayani ke sikap melayani. Mereka harus sadar bahwa sekarang bukan lagi zaman feodal.
Di mana elite pemerintahan seolah raja yang maunya dilayani rakyat. Mereka juga semestinya memaknai pemilu bukan sebagai alat untuk persaingan perebutan kekuasaan. Tetapi, lebih kepada sebuah jalan untuk melakukan pengabdian kepada rakyat.
Pengabdian ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Mewujudkan konsep negara-kesejahteraan (welfare-state) yang selama ini didambakan. Seperti meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, dan upaya-upaya lain dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tentu saja, layaknya sebuah pengabdian, maka harus dilakukan tanpa pretensi dan tidak mengharap pamrih.
Jika ada kesadaran kolektif dari para kontestan elite politik, tentu kerja KPU menggelar pemilu lebih mudah. KPU tidak perlu lagi teriak-teriak kepada pemilih untuk menghindari politik transaksional. KPU bisa lebih fokus menyiapkan seluruh prosedur pemilu yang menjamin kesetaraan dan perlakuan sama bagi peserta pemilu.
Meski demikian, KPU harus menjaga independensinya. Tidak ikut terseret arus keberpihakan kepada warna partai politik tertentu. KPU harus memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh peserta pemilu. Agar terwujud pemilu yang sejati (genuine election).
Kesadaran memahami makna filosofis pemilu diharapkan menghasilkan output elite pemimpin berkualitas. Pemimpin yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sehingga, dampak yang dirasakan masyarakat terkait dengan peningkatan kualitas hidupnya akan benar-benar terasa.
Momentum Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Kepala Daerah 2024 harus dijadikan titik tolak untuk memulainya. Mari kita kawal agar berjalan sesuai on the track. Sudah tiba saatnya bagi kita semua untuk menahan dan mengendalikan diri. Awali dengan tindakan untuk tidak memilih calon wakil rakyat yang berlaku politik transaksional.
Bahasa sederhananya, jangan memilih kontestan yang memberikan uang/barang untuk membujuk kita agar memilihnya. (*)
*)Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
Sekretariat KPU Kota Pasuruan